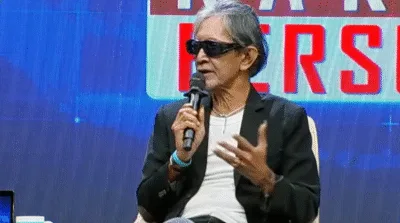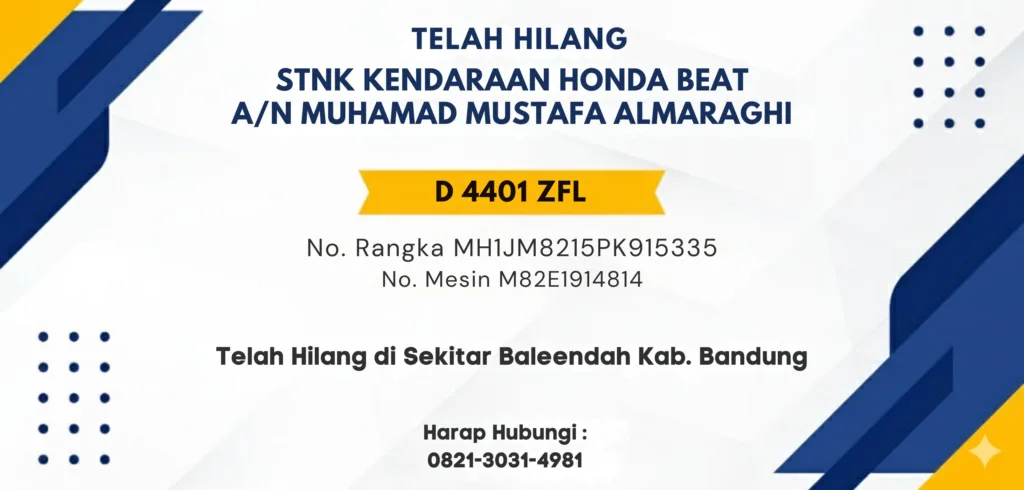Oleh Yanti Lawerissa, D.J.A. Hehanussa, E.R.M. Toule, Abraham Tulalessy
KEKAYAAN mineral Indonesia terus berkonflik dengan tujuan hijau negara ini. Meskipun undang-undang baru telah disahkan untuk mengatur pertambangan serta melindungi lingkungan dan masyarakat lokal, penerapannya masih lemah.
Di Pulau Buru, petani eukaliptus Mahani beralih profesi menjadi penambang emas untuk memperoleh pendapatan lebih. Ia hanyalah salah satu dari banyak orang yang ikut serta dalam demam emas yang dimulai pada 2011, ketika emas ditemukan di Gunung Botak. Sejak saat itu, orang-orang dari seluruh Kepulauan Maluku berbondong-bondong ke pulau tersebut untuk mencari emas.
Sebelumnya, Pulau Buru dikenal dengan stigma sebagai tempat pengasingan bagi tahanan politik yang merupakan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1965. Peristiwa itu mengakibatkan pembantaian massal terhadap simpatisan PKI, di mana lebih dari 500.000 orang meninggal.
Gunung Botak di Maluku menggambarkan kompleksitas tata kelola pertambangan di Indonesia. Sejak emas ditemukan pada 2011, daerah tersebut berubah drastis — dari wilayah pertanian menjadi pusat pertambangan skala kecil yang tidak teratur. Ribuan penambang datang, sebagian besar tanpa izin resmi, dan kegiatan pertambangan dilakukan dengan cara yang merusak lingkungan.
Penggunaan merkuri dan sianida yang berlebihan dalam proses pertambangan telah mencemari sungai, merusak ekosistem, dan mengancam kesehatan masyarakat.
Namun, akar permasalahan tidak hanya terletak pada perilaku penambang ilegal. Regulasi negara yang seharusnya berfungsi sebagai pelindung justru membuka peluang eksploitasi.
Keterasingan Masyarakat Lokal dan Bencana Ekologis
Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang disahkan pada 2009 untuk memperkuat perlindungan lingkungan dan hak masyarakat, direvisi pada 2020. Revisi ini memperluas wewenang pemerintah pusat dan mempermudah pemberian izin pertambangan.
Pasal 35 dalam UU Minerba menyatakan bahwa izin pertambangan dapat diberikan oleh pemerintah pusat tanpa kewajiban untuk berkonsultasi dengan pemerintah daerah atau masyarakat yang terdampak. Hal ini menghilangkan mekanisme kontrol lokal dan melemahkan partisipasi publik. Dalam konteks Gunung Botak, pemerintah daerah memiliki pengetahuan lapangan dan hubungan langsung dengan masyarakat lokal. Ketika wewenang mereka dibatasi, pengawasan menjadi lemah dan konflik sosial meningkat.
Selain itu, Pasal 136 UU Minerba mengatur bahwa pemegang izin pertambangan wajib memperoleh persetujuan dari pemegang hak atas tanah. Namun, tidak ada penjelasan rinci mengenai bentuk persetujuan, mekanisme verifikasi, atau perlindungan terhadap tanah adat. Akibatnya, perusahaan pertambangan dapat mengklaim telah memperoleh persetujuan berdasarkan dokumen administratif semata, tanpa proses konsultasi yang sah. Hal ini membuka pintu untuk pengambilalihan tanah dan marginalisasi masyarakat adat.
Di Gunung Botak, masyarakat adat dan petani lokal kehilangan akses ke tanah produktif. Meskipun tambang emas ditutup pemerintah pada 2015, kegiatan pertambangan ilegal tetap berlanjut. Penegakan hukum tidak efektif, dan sanksi kriminal terhadap pelaku pencemaran lingkungan tidak memberikan efek jera. Bahkan, denda yang dijatuhkan seringkali tidak dibayar, tanpa konsekuensi hukum yang jelas. Ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan ketidakmampuan regulasi untuk melindungi kepentingan publik.
Reformasi Hukum yang Diperlukan
Dari perspektif hukum lingkungan, UU Minerba juga tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan ekologi yang tercantum dalam undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berlaku sejak 2009. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap lingkungan harus melalui proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Namun, dalam praktiknya, banyak proyek pertambangan disetujui tanpa AMDAL yang memadai, atau dengan dokumen yang hanya menjadi formalitas.
Di Gunung Botak, penggunaan merkuri dan sianida tidak terkendali. Sungai Waekase dan Anahoni, yang mengalir melalui Gunung Botak, tercemar parah. Penelitian oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menunjukkan bahwa kadar merkuri di Sungai Waekase telah mencapai 0,05 mg/L — 50 kali lebih tinggi dari ambang batas aman WHO. Dampaknya tidak hanya pada ekosistem, tetapi juga pada kesehatan manusia. Merkuri dapat menyebabkan gangguan neurologis, kerusakan ginjal, dan gangguan perkembangan pada anak-anak. Namun, tidak ada mekanisme pemulihan lingkungan yang sistematis.
Hukum Lingkungan juga mengatur partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pasal 65 menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi mengenai lingkungan, berpartisipasi dalam pengelolaannya, dan mengajukan keberatan terhadap rencana kegiatan yang berdampak. Namun, dalam konteks pertambangan, hak ini sering diabaikan. Proses pemberian izin pertambangan tertutup, dan masyarakat yang terdampak tidak terlibat secara signifikan. Ketika polusi atau konflik terjadi, akses ke keadilan sangat terbatas.
Pemerintah daerah dihadapkan pada dilema. Di satu sisi, tambang menghasilkan pendapatan melalui pajak dan retribusi. Di sisi lain, mereka harus menanggung dampak sosial dan ekologi yang ditimbulkan. Tanpa dukungan regulasi yang kuat, pemerintah daerah kesulitan menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan keberlanjutan. Ketika wewenang mereka dikurangi oleh UU Minerba, ruang gerak untuk melindungi masyarakat dan lingkungan menjadi terbatas.
Kesimpulan dan Jalan ke Depan
Situasi ini menunjukkan bahwa pertambangan memang bisa memberikan mata pencaharian, tetapi tidak tanpa regulasi yang tepat. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali akan terus berlangsung.
Beberapa reformasi regulasi seperti pengakuan penuh atas hak masyarakat adat atas tanah adat, dengan mekanisme persetujuan yang jelas dan mengikat secara hukum, sangat dibutuhkan. Regulasi juga harus memastikan bahwa tanah adat tidak dapat dialihkan tanpa proses konsultasi dan persetujuan bersama.
Pengawasan lingkungan, termasuk larangan penggunaan merkuri dan sianida, serta penerapan teknologi pengolahan tailing yang aman juga perlu dilakukan. Pemerintah harus menyediakan anggaran dan sumber daya untuk memantau dampak pertambangan secara rutin.
Penegakan hukum yang tegas dan konsisten, dengan sanksi kriminal dan administratif yang efektif terhadap pencemar dan penambang ilegal harus dipastikan. Denda harus dibayar sepenuhnya, dan dana tersebut harus digunakan untuk pemulihan lingkungan dan kompensasi bagi masyarakat yang terdampak.
Peta jalan nasional untuk reformasi pertambangan, yang berbasis pada data ilmiah dan melibatkan akademisi, masyarakat sipil, dan komunitas lokal, dapat memastikan bahwa sistem pertambangan adil, transparan, dan berkelanjutan.
Sinkronisasi antara UU Minerba dan UU Perlindungan Lingkungan akan membantu mengintegrasikan prinsip kehati-hatian, partisipasi publik, dan pemulihan ekologi serta menjadi bagian dari kebijakan pertambangan.
Tanpa perubahan regulasi yang menguntungkan lingkungan dan masyarakat, UU Minerba akan terus menjadi alat legalisasi kehancuran. Indonesia memerlukan kebijakan pertambangan yang tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga menjamin keadilan ekologi dan sosial.
Gunung Botak hanyalah salah satu dari banyak contoh.
Di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, cerita serupa terus berulang. Jika tidak segera ditangani, kerusakan lingkungan akan terus meluas, dan generasi mendatang akan mewarisi tanah yang tercemar dan konflik yang belum terselesaikan.***
- Yanti Lawerissa, D.J.A. Hehanussa, dan E.R.M. Toule adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.
- Abraham Tulalessy adalah dosen di Fakultas Pertanian Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.
- Moh Ilias Bin Hamid adalah mahasiswa doktoral di Fakultas Hukum, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.
- Awalnya diterbitkan di bawah lisensi Creative Commons oleh 360info™.